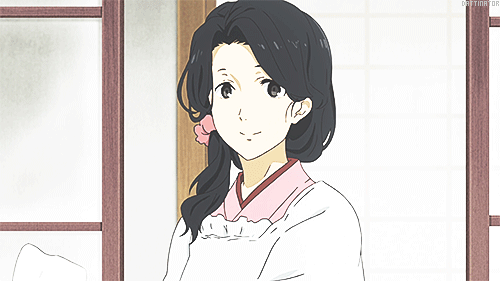
Rindu yang Kusimpan Untukmu
Hujan baru saja reda
seiring langkah ringan milik seorang gadis yang membawa tubuh ramping itu melewati
sebuah gerbang masuk yang terbuat dari kayu. Di balik gerbang setinggi 3 meter
itu terhampar sebuah pekarangan dengan bangunan rumah megah di ujungnya. Payung
putih yang masih basah sudah terlipat dan tergenggam erat di tangan kiri.
Setelah berjalan beberapa meter dari gerbang, melewati taman dengan kolam di
sebelah kiri dan barisan pepohonan di sebelah kanan, gadis yang masih memakai
seragam sekolah itu berhenti tepat di depan beranda. Selepas berganti alas kaki
dari sepasang sepatu hitam menjadi sandal dalam ruangan, dengan kaos kaki yang
masih terpakai, dia berjalan menyusuri koridor yang mengarah ke bagian sebelah
kiri rumah besar tersebut. Menuju ke sebuah ruangan berukuran 4x5 meter yang
terletak di ujung koridor.
“Ah, hari ini
sungguh melelahkan,” gumam gadis itu sambil merebahkan diri. Rambutnya yang
panjang sudah terurai setelah tangannya dengan cekatan melepaskan ikat rambut yang
dari tadi pagi mengubah rambut hitam berkilau itu menjadi gaya ekor kuda.
Setelah beberapa
menit tak bergeser dari atas kasur, tangannya meraih sesuatu dari atas meja.
Sebuah ponsel berwarna hitam yang langsung dia serang dengan hentakan kedua
jempolnya. Sebuah pesan baru saja terkirim ke salah satu ID yang ada di daftar
kontaknya.
To : Rka
Text : Apakah kau
sudah sampai rumah?
Tak butuh waktu
lama, ponsel itu bergetar. Sebuah pesan baru telah masuk.
From : Rka
Text : Ya, baru
saja. Masih rebahan di atas tempat tidur. Bagaimana denganmu?
To : Rka
Text : Aku juga. Sedikit
malas untuk beraktivitas. Hari ini aku benar-benar lelah.
From : Rka
Text : Dasar, hari
ini kau terlalu bersemangat. Beristirahatlah. =]
To : Rka
Text : Ah, soalnya tadi benar-benar menyenangkan. Ya, terima kasih. ^_^
“Dasar,” ucap gadis itu lirih. Ada senyum ditambah rona merah di wajahnya.
Sesi obrolan singkat itu berakhir. Ponsel hitam itu tak lagi bergetar tanda tak ada lagi pesan masuk, sementara pemiliknya nampak mulai kehilangan kesadaran. Rasa kantuk mulai menyergap gadis itu dan perlahan menariknya ke alam mimpi.
Airin yang nampak begitu tenang dalam tidurnya tak menyadari kehadiran seseorang yang dari tadi memperhatikannya sejak memasuki pekarangan. Sosok yang tak lebih tinggi dari Airin itu berjalan mendekat ke tempat tidur Airin. Mengusap pucuk rambut Airin sambil tersenyum. Dengan lembut, sebuah kecupan menyentuh dahi Airin yang tak tertutup poni. Membuat Airin terbangun.
“Hah?” Airin mengucek kedua matanya. Perlahan, tangan kanannya bergerak mengusap dahi yang kini tertutup poni panjangnya yang menjulur turun. Ada sesuatu yang tiba-tiba mengganggu perasaannya. Dia tersenyum. “Mungkin hanya perasaanku saja.”
***
“Selamat siang,”
sapa seseorang dari arah pintu. Seorang pemuda yang dari tadi duduk sendirian
di dalam ruangan itu menoleh sembari menutup buku di hadapannya.
“Siang, Airin. Kau
sendirian?”
“Hai, Raka. Andi
mendapatkan tugas piket perpustakaan hari ini, jadi dia akan terlambat.” Airin
mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan sambil duduk tepat di hadapan Raka
yang perlahan mulai membuka kembali buku bersampul hijau di hadapannya.
“Kau sudah cukup
beristirahat bukan?”
“Ah, iya. Praktek olahraga
kemarin benar-benar melelahkan. Tapi menyenangkan.” Airin menunduk berusaha
menyembunyikan rona merah di wajahnya.
Mata Raka melirik ke
arah Airin yang tiba-tiba terlihat gelisah sambil sesekali mencuri pandang ke
arahnya. Seolah mengerti jalan pikiran Airin, pemuda itu mengeluarkan sesuatu
dari tas ransel yang bersandar di kaki kursinya. Sebuah kotak berwarna merah
dengan plastik bening yang masih membungkusnya dengan rapi. Dengan cekatan, dia
merobek plastik itu lalu membuka kotak tersebut. Memamerkan bagian bersekat
yang masing-masing terisi oleh bentuk-bentuk menarik.
“Camilan. Kau mau?” Raka
menggesernya sedikit ke hadapan Airin.
“Coklat!” pekik
Airin.
Raka tersenyum melihat mata Airin yang berbinar ditambah senyum yang terlukis di wajahnya. Jika sudah seperti ini, dia bisa dengan tenang membaca karena Airin tidak akan merespon pembicaraan apapun ketika sudah berhadapan dengan coklat. Kecuali jika dia sendiri yang mengajak bicara. Tapi sepertinya, kali ini perkiraan Raka meleset. Senyum Airin yang tadi mengembang tiba-tiba surut berubah menjadi raut murung. Raka kembali menutup bukunya.
“Ada apa? Tumben sekali tidak bersemangat di hadapan sekotak coklat?” Raka dapat melihat kesedihan yang sedang Airin coba sembunyikan.
“Ah, tidak. Coklat ini
enak sekali, seperti yang selalu kau bawa ke sini. Hanya saja ….” Kalimat Airin
menggantung. Dia menghela napas lalu melanjutkan, “aku rindu ibuku.”
Suasana berubah hening. Terdengar helaan napas Raka selepas mendengar pernyataan Airin. Raka teringat, sebentar lagi adalah hari ulang tahun ibu Airin, sekaligus hari di mana 5 tahun yang lalu beliau, ibunda Airin, meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Jantung Raka serasa diperas ketika melihat mata Airin yang mulai sembab. Terlebih ketika dia ingat bagaimana perubahan sikap Airin yang cukup kontras selepas kehilangan ibunya. Raka harus meluangkan waktu sepulang sekolah menunggu Airin duduk diam di depan nisan ibunya tanpa berbuat apa pun lalu mengajaknya untuk pulang. Begitu seterusnya hingga keluarga besar Airin memutuskan untuk membuatnya tinggal di tempat kakeknya.
“Kau ingin mengunjungi makam beliau?” tanya Raka. Mata Airin melebar.
“Ya! Aku ingin ke
sana! Tapi ….”
“Tenang saja, aku yang
akan bicara kepada kakekmu,” ujar Raka menenangkan.
“Terima kasih, Raka,”
kata Airin senang. Raka tersenyum.
“Apa coklatnya enak?”
tanya Raka sambil mengambil sebuah coklat berbentuk hati. Airin yang sibuk
mengunyah coklat di mulutnya hanya memberikan anggukan sebagai jawaban.
***
Sudah sejak pagi Raka dan Airin duduk di ruang tunggu stasiun kota. Sesuai dengan rencana, hari ini mereka akan pergi ke tempat ibu
Airin dimakamkan. Sudah 3 tahun sejak Airin pindah dan dia
belum pernah kembali untuk mengunjungi makam ibundanya. Meski sudah berkali-kali berusaha meyakinkan kakeknya yang kolot agar mengizinkannya pergi, berkali-kali pula kakeknya dengan tegas melarang Airin untuk pergi. Dan hari ini, berkat Raka, dia
dapat pergi berkunjung.
Raka dan Airin berjalan bersisihan menuju ke sebuah kereta yang baru saja datang. Mereka kemudian masuk ke dalam gerbong yang nampak tidak terlalu sesak. Raka segera mencari tempat duduk yang kosong untuk mereka berdua. Perlahan, kereta tersebut mulai berjalan. Kaki-kaki kokohnya mulai berderap di atas lintasan baja dengan mantap.
Raka dan Airin yang duduk berhadapan lebih banyak menghabiskan waktu dengan memandang ke luar jendela. Ada banyak hal yang saat ini berkelebat di dalam kepala mereka masing-masing. Sesekali mereka mengobrol, tapi kemudian kembali dalam hening. Airin terlihat senang, tapi juga terlihat tak tenang. Sementara Raka yang sesekali melirik ke arah Airin juga memikirkan sesuatu yang mengganggunya sejak pagi tadi.
“Rin, kau mau?” Raka menyodorkan sebuah kotak bekal berisi bermacam-macam kue kering kepada Airin.
“Ah, ya. Terima kasih.”
Tangan Airin segera mengambil sebuah kue lalu memakannya.
“Sebentar lagi
sampai.”
“Iya.”
***
Setelah berganti
kendaraan dengan naik sebuah bus kemudian berjalan beberapa ratus meter dari
sebuah halte, Raka dan Airin tiba di depan sebuah komplek pemakaman umum. Sebuah
gapura besi yang berdiri angkuh terasa menyambut kedua tamunya dengan tatapan
dingin. Setelah memantapkan hati, Airin melangkah melewati gapura itu diikuti
Raka yang segera menyesuaikan langkah dan berjalan di sebelahnya.
Langkah Raka dan Airin terhenti di depan sebuah nisan yang terbuat dari marmer putih. Sebuah nama dan tanggal terukir di atasnya. Dengan perlahan, Airin membungkuk lalu duduk di hadapan nisan tersebut. Diikuti Raka yang sudah duduk di sebelahnya, Airin memejamkan kedua mata lalu mulai memanjatkan doa. Kemudian menaburkan bunga yang sudah dia siapkan sebelumnya.
Setelah merasa cukup, Airin berdiri dan berniat berjalan pergi sebelum pergelangan tangannya terasa ditarik. Raka menahannya.
“Airin. Sudah 3 tahun sejak terakhir kali kau ke sini. Apakah kau tidak ingin berada di sini sedikit lebih lama?” tanya Raka sambil menatap punggung kecil Airin.
“Aku hanya tidak
ingin lagi larut dalam kesedihan, Ka. Itu saja.”
“Kau yakin ingin
begitu?” tanya Raka lagi. Dia sudah melepaskan tangan Airin dari genggamannya.
“Ya. Bukankah akan
merepotkan jika kau harus menunggu dan merayuku agar mau pulang seperti dulu?”
Lagi-lagi ada sesuatu yang terasa menekan dari dalam dada Raka. Terlebih ketika dia
melihat air mata Airin yang sudah jatuh saat Airin menoleh ke arahnya.
“Jangan bohong! Hanya
dengan sekali lihat pun aku bisa tahu kalau kau sangat ingin berada di sini
lebih lama!” Raka tak dapat menahan dirinya untuk tidak meluapkan perasaannya. Membuat
Airin tersentak kaget.
“Kenapa kau
memarahiku? Apakah salah jika aku tidak ingin merepotkanmu? Aku sudah dewasa!
Aku berhak melakukan apa yang ingin kulakukan!” kata Airin tak mau kalah. Kali ini dia sepenuhnya berdiri menghadap Raka. Kesedihan,
kemarahan, keraguan, kepedihan, semua tergerus menjadi satu di suara paraunya.
“Lalu, apakah salah jika aku mempedulikanmu? Hanya ini yang bisa kulakukan untukmu,” ucap Raka lirih. Dia tertunduk. Airin terdiam.
“Aku … hanya merasa …
kesepian,” ucap Airin terbata-bata.
“Aku ada di sini,
Airin. Apa kau juga ingin membuangku?” Mendengar
pertanyaan Raka, Airin tercekat. Kali ini dia yang merasakan jantungnya ditekan
kuat-kuat.
“Tidak! Aku hanya …
aku ….” Airin mendekat satu langkah ke arah Raka. Suasana berubah
hening.
“Bolehkah aku …
memanggilmu seperti dulu?”
“Aku tidak keberatan.”
Seolah adegan lambat dalam sebuah film, tangan Airin menyentuh dada bidang Raka lalu membenamkan wajahnya di situ. Isak tangisnya perlahan terdengar jelas. Seiring bisikan lirih yang juga berubah menjadi suara penuh kepedihan.
“Aku … aku merindukan ibu, kak! Aku merindukan ibu. Kak Raka, aku ingin bertemu lagi dengan Ibu!” Suara penuh kerinduan yang putus asa itu memecah kesunyian.
Tanpa kata, Raka meraih tubuh mungil Airin lalu mendekapnya dengan erat. Tak ada yang bisa dia lakukan selain mencurahkan seluruh waktu yang dia punya untuk adik yang paling dia sayangi. Apalagi setelah seluruh keluarganya menyalahkan dirinya akibat kecelakaan yang menghilangkan nyawa ibu Airin, yang juga ibunya. Seluang apa pun waktu, dia akan habiskan untuk berada di dekat Airin.
“Maafkan kakak, Rin. Seharusnya kakak yang terbaring di sini, bukan ibu. Maafkan kakak,” ucap Raka sambil memeluk erat Airin.
“Kak, kau tidak
salah. Ini sudah takdir yang tidak bisa dihindari. Terima kasih karena selama ini
sudah dengan tulus menjagaku.” Airin menyeka air mata Raka.
“Terima kasih, Rin. Kau
benar-benar tumbuh menjadi gadis yang baik,” ucap Raka sambil tersenyum. Pipi Airin
memerah mendengar pujian Raka.
Dengan mata yang masih merah dan wajah yang masih basah dengan air mata, dua orang yang selama ini menyembunyikan kenyataan bahwa mereka adalah kakak beradik tersebut saling tersenyum satu sama lain. Tapi senyum di wajah salah satu dari mereka tiba-tiba lenyap.
“Maafkan Ibu yang tiba-tiba pergi meninggalkanmu, Raka. Terima kasih kau sudah menjaga Airin dengan seluruh waktumu. Kau menepati janji yang pernah kau buat, Nak. Kau benar-benar anak lelaki kebanggaan Ibu.”
Dari sudut matanya, tepat di belakang Airin, Raka tercekat tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sosok yang sangat dia cintai dan rindukan lebih dari siapapun kini muncul di hadapannya. Ibu yang sudah pergi dari sisinya beserta kenangan yang selama ini dia buang jauh-jauh tiba-tiba menampakkan diri di depan mata kepalanya.
Raka kecil berlarian di dalam rumah sambil membawa pesawat mainannya. Tanpa dia sengaja, dia menabrak lego berbentuk rumah yang sedang disusun oleh seorang gadis kecil. Airin kecil yang melihat rumah yang tadi dia susun rusak menangis sejadi-jadinya. Hal itu mengundang ibu mereka segera berlari mendekat.
“Raka, kenapa Airin menangis? Apa yang sudah kau lakukan?” selidik
Ibu kepada Raka. Meski nampak
sedang memarahi putranya, tapi nada suara wanita berpakaian sederhana itu
sangatlah lembut. Terdengar begitu bersahaja.
“Aku … aku. Aku merusak rumah yang dibuat Airin! Maafkan aku, Bu,” jawab Raka kecil sambil sesenggukan.
Dengan tatapan teduh, Ibu dengan lembut menarik kedua buah hatinya yang masih menangis ke dalam pelukannya lalu mengusap dengan penuh kasih sayang kepala
mereka. “Raka, berjanjilah kepada Ibu jika nanti Ibu tidak bisa lagi menjaga
kalian, kau harus menjaga Airin. Kau menyayangi Airin, bukan?”
“Tentu saja, Bu! Aku berjanji, aku akan menjaga Airin dengan
seluruh kekuatanku!” kata Raka kecil sambil menepuk dadanya dengan kepalan
tangan kecilnya. Hal itu mengundang tawa Ibu. Juga Airin yang nampak kagum dengan suara lantang dan mantap kakaknya, Raka.
“Kau adalah anak lelaki kebanggaan Ibu, Raka.”
Senyum menenangkan dari wajah yang sangat dia rindukan itu membuat Raka tak kuasa menahan air matanya. Dia menangis hingga jatuh bertumpu lutut. Beban yang selama ini menumpuk di dalam dadanya perlahan luruh bersama isak tangis dan air matanya yang jatuh berderai.
Airin yang terkejut menoleh ke arah Raka memandang. Di sana, meski tak terlalu ingat, Airin dapat mengenali wajah itu. Dia tersenyum. Sambil mengusap dahinya, Airin berkata, “Jadi, waktu itu Ibu yang mengecup dahiku?”
Anggukan kecil cukup memberikan Airin jawaban. Dia berbalik kemudian memeluk erat kakaknya yang masih menangis. “Terima kasih, kak. Sekarang, menangislah untuk dirimu sendiri. Lepaskanlah semua beban yang selama ini kau simpan sendiri.”
Bersamaan dengan Raka yang mulai menegakkan kepalanya, sosok wanita paruh baya yang tersenyum penuh kedamaian itu perlahan mulai memudar menjadi bayang. Dengan tangan saling menggenggam erat, Raka dan Airin melepas kepergian itu dengan air mata yang masih mengambang, tapi juga dengan senyum penuh keikhlasan.
Menanggung beban seorang diri untuk waktu yang lama bukanlah hal yang mudah, tapi demi seseorang yang berarti, hal tanpa terasa akan begitu saja terlewati. Sementara memendam kesedihan akibat ditinggal pergi seseorang yang dicintai akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Hanya dengan keikhlasan, beban dan kesedihan yang terpendam akan menghilang. Jadi, sudahkah kau mengikhlaskan kehilangan yang kau dapatkan?
~ fin


