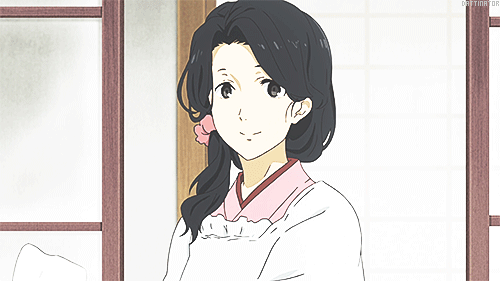Gloomy Spring
“Ini teh anda, o hime-sama,” ucap seorang pemuda berpakaian
pelayan sambil meletakkan sebuah nampan dengan secangkir teh di atasnya.
“Oreki, kita hanya berdua. Apa kau lupa dengan permintaanku waktu itu?”
Seorang gadis dengan rambut panjang yang hitam berkilau nampak merajuk. Memasang
wajah yang ditekuk.
Oreki Houtarou, pemuda itu, hanya bisa menghela napas mendengarnya. “Baik-baik.
Maafkan aku, Chintanda.” Chintanda Eru, tersenyum. Dia meraih cangkir itu lalu
meminumnya hingga tersisa setengah, lalu meletakkannya lagi.
“Jadi, bagaimana perkembangan terakhir dari novel yang kau tulis? Aku
dengar sudah memasuki bab terakhir?” Oreki sudah bisa menduganya. Sebuah
pertanyaan pembuka yang akan menarik lebih banyak pertanyaan baru jika dia
tidak pandai-pandai mencari jawaban yang ‘tepat’.
“Hampir selesai. Tinggal memasukkan unsur kejutan sebagai pukulan
terakhir lalu membuat ending yang sesuai agar tidak menghancurkan
keseluruhan cerita.” Oreki menjatuhkan dirinya di teras kayu di depan pintu
kamar Chitanda. Matanya menatap kosong halaman belakang yang luasnya hampir
setara dengan rumahnya.
“Unsur kejutan? Pukulan terakhir?” Chitanda tak henti-hentinya
menggumamkan kata-kata itu. Sesuatu yang asing bagi orang sepertinya. Tanpa
disadari Oreki yang masih menikmati kekosongan dalam lamunan, Chitanda
merangsek mendekati pintu. Mendekatinya.
Oreki menoleh, mendapati Chitanda yang kepayahan bergerak dengan selimut
yang masih membungkus tubuhnya. Reflek, dia bangkit kemudian meraih tubuh lemah
itu ke dalam pelukannya. Menuntunnya kembali ke futon yang masih hangat
karena baru saja ditinggalkan beberapa menit saja.
“Jangan sembrono, Chitanda! Lain kali panggil saja aku! Kau tidak perlu
susah payah bergerak seperti ini!” Nampak kegusaran di wajah Oreki yang
biasanya hanya menampilkan ekspresi datar seperti kayu dengan mata seperti milik
ikan mati. Dan semua itu tertangkap jelas oleh iris ungu Chitanda yang
pelupuknya mulai terasa panas. Sementara Oreki, dengan lembut membantu Chitanda
rebah lalu menyelimutinya.
Hening memasuki kamar luas itu. Mengubah musim semi yang seharusnya terasa
hangat menjadi dingin dan menusuk. Setidaknya di antara Oreki dan Chitanda. Membawa
mereka ke dalam lamunan masing-masing. Namun, apa yang mereka pikirkan kurang
lebih sama
Mereka bertemu di awal musim dingin ketika keluarga Chitanda sedang
mencari pelayan pribadi untuk merawat Chitanda yang memiliki kondisi tubuh yang
lemah. Di saat itulah Irisu Fuyumi, putri dari salah satu kenalan keluarga Chitanda
mengenalkan sosok Oreki Houtarou kepada mereka.
Awalnya, keluarga Chitanda kurang menerima karena mereka menghendaki
pelayan wanita. Tapi setelah diyakinkan oleh Irisu, mereka pun luluh. Akhirnya,
Oreki pun bekerja sebagai pelayan pribadi sekaligus penjaga Chitanda Eru, sang
tuan putri. Dan ketika mereka hanya berdua saja, Oreki akan berubah menjadi
sosok yang lain. Seorang teman. Seorang yang selalu menceritakan hal-hal
menarik. Seorang yang tak pernah jemu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia
tanyakan sekalipun itu membosankan. Dan, yang tidak diketahui oleh banyak
orang, bahkan oleh Oreki, Chitanda sudah menganggapnya sebagai sosok yang
sangat dia kagumi. Yang dia cintai.
Yang belum lama ini terjadi, adalah ketika pohon sakura di halaman
belakang mekar. Mata ungu Chitanda tiba-tiba bersinar dan sama sekali tidak
menyiratkan sorot mata seseorang dengan keadaan yang sangat lemah. Dan dengan rasa
keingintahuannya yang sangat besar, Chitanda memberondongnya dengan berbagai
pertanyaan tentang sakura.
“Oreki, kenapa pohon itu baru mekar di musim semi?”
“Oreki, apakah dia bisa mekar di musim lain?”
“Oreki, kenapa warnanya bisa seindah itu?”
“Oreki, bagaimana rasanya duduk di bawah sana?”
“Oreki, maukah kau duduk di sana denganku?”
Ah, pertanyaan terakhir itu sepertinya hanya ada di dalam ruang imaji
Oreki yang saat ini tiba-tiba terkekeh. Dia sudah kembali dari lamunannya. Dari
ekor mata, dia dapat melihat wajah Chitanda yang nampak sedang tertidur. Dia
menghela napas. Memerintahkan kepanikan yang tadi sempat merayapinya agar
segera pergi dan menghilang. Lalu dia teringat sesi penutup tanya jawab saat
itu. Perubahan peran. Oreki menjadi bagian penanya.
***
“Chitanda. Apakah kau merasa bahagia menjalani hidup seperti ini?”
Sebuah pertanyaan yang langsung mengenai sasaran. Chitanda seperti tertohok. Ada
rasa menyesal yang muncul di hati Oreki. Ingin sekali dia meralat pertanyaan
itu, tapi buru-buru dia batalkan ketika Chitanda sudah mulai bicara.
“Aku tidak bahagia.” Oreki tercekat.
“Chitanda, maaf. Kau tidak harus-“
“Hanya bisa terbaring di sini menunggu belas kasihan orang lain. Tidak bisa
menjalani hidup layaknya orang normal. Aku sama sekali tidak bahagia, Oreki. Terkadang,
aku benar-benar ingin mati.” Chitanda tersenyum. Sebuah senyum penuh kegetiran.
“Tapi … baru-baru ini aku mulai merasa bahagia. Terlebih setelah kau
hadir.” Kalimat terakhir diucapkan dengan suara yang amat lirih. Membuat Oreki
harus memelengkan kepalanya untuk berusaha menangkap suara itu.
“Ha?”
“Oreki. Aku ingin menjadi seperti sakura. Meskipun hanya mekar di musim
semi dan lenyap bahkan sebelum musim semi berakhir, sakura selalu bisa terlihat
indah. Begitu hidup. Dan saat ini, aku merasa benar-benar hidup, Oreki. Terima kasih.”
Chitanda menutup kalimatnya dengan sebuah senyuman yang nampak begitu bersinar
di mata Oreki.
“Terima kasih?” Oreki tidak mengerti. Chitanda seolah enggan menjawab
ketidakmengertian Oreki dan hanya tertawa kecil.
***
“Kau belum menghabiskan tehmu,” ucap Oreki lirih sambil menarik nampan
dengan secangkir teh di atasnya. Yang sudah dingin.
Tepat sebelum dia bangkit dan beranjak dari sisi Chitanda, Oreki
merasakan sesuatu yang menarik ujung lengan panjang bajunya. Tangan mungil
Chitanda. Sebuah tarikan yang sangat lemah, yang meskipun dapat dengan mudah
dilepas, Oreki memilih untuk kembali duduk. Meraih tangan itu lalu
menggenggamnya. Erat.
“Maafkan aku, hime. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita.” Oreki
mengangkat tangan itu ke depan wajahnya lalu menciumnya. Lembut. Membuat Chitanda
terbangun tanpa disadari.
“Oreki?” ucap Chitanda lirih. Oreki menyambut wajah yang masih dikuasai
kantuk itu dengan sebuah senyuman. Berusaha menyamarkan air mata yang tadi
sempat jatuh.
“Maaf sudah membangunkanmu.”
“Oreki, bolehkah aku meminta kau melakukan sesuatu?” tanya Chitanda. Ada
keraguan yang tersirat di dalam suara itu. Juga kelemahan.
“Kenapa kau harus bertanya? Apapun akan kulakukan untukmu hime- Chitanda.
Apa itu?” Oreki membantu Chitanda untuk duduk.
“Tolong bawa aku keluar. Ke bawah pohon sakura itu.” Sebuah permintaan
sederhana yang terlontar dengan suara yang seolah sedang meminta kehidupan. Oreki
merasakan ada yang tidak beres. Tapi dengan segenap tenaga, dia berusaha
mengabaikannya.
Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Oreki mengangkat tubuh Chitanda dari futon.
Membawanya dengan perlahan keluar dari ruangan luas yang terasa sunyi itu. Tubuh
lemah itu terasa begitu ringan dan juga rapuh. Dengan mantap, Oreki terus
berjalan melewati pintu, menuju jalan setapak di halaman belakang itu, lalu
berhenti di bawah kelopak-kelopak sakura.
“Kita sudah sampai.” Dengan perlahan, Oreki menurunkan Chitanda. Membiarkannya
duduk bersandar di batang kokoh sakura. Lalu dia jongkok bertumpu satu lutut di
hadapannya.
“Oreki, maukah kau mendengarkan permintaanku?”
“Tentu, akan kudengarkan.”
“Tapi … tolong dengarkan permintaan ini sebagai sebuah permintaan dari
seorang Chitanda Eru, seorang gadis biasa bukan seorang tuan putri. Dan aku
meminta jawaban dari seorang Oreki, bukan seorang pelayan tuan putri. Bisa?”
Napas Oreki tertahan. Sebuah permintaan bersifat personal!
“Y-Ya.” Oreki tidak bisa menyembunyikan kegugupannya.
“Oreki Houtarou. Aku …”
Sesak mulai memenuhi seisi dada Oreki. Terlebih ketika tubuh Chitanda
mulai condong ke arahnya. Tak lagi bersandar.
“… selama ini …”
Detak jantungnya mulai berakselerasi.
“… aku men-“
Chitanda ambruk di pelukannya. Tepat sebelum kalimat itu selesai diucapkan. Jantung Oreki seperti hendak melompat
keluar. Dengan sigap dia meraih bahu Chitanda dan memeriksa raut mukanya. Sangat
pucat dengan napas yang tersengal. Denyut nadinya juga sangat lemah. Dan semakin
lemah.
“Chitanda! Bertahanlah! Chitanda!!”
***
Oreki yang masih dibalut setelan hitam-hitam duduk sendirian di teras
kayu di depan kamar Chitanda. Matanya menatap kosong halaman luas yang kini
terasa jauh lebih kosong. Hanya pohon sakura yang saat ini sedang mekar,
satu-satunya entitas tersisa yang bisa dia nikmati. Meskipun, tidak dapat
dipungkir, warna sakura yang mekar musim semi kali ini jauh berbeda. Terlihat
kusam. Abu-abu. Itulah yang ditangkap oleh mata sembab Oreki.
Di tangan kanannya, sebuah buku berukuran sedang dengan halaman yang tak
terlalu tebal terbuka tepat di bagian tengahnya. Mata Oreki sudah beralih dari
sakura kusam di hadapannya ke sebuah kertas kecil berisi pesan singkat yang ada
di halaman itu.
Terima kasih
atas peran yang kau mainkan.
Dengan ini,
kau dan keluargamu bebas dari semua hutang dan hukuman.
Kau boleh pergi sekarang.
Oreki menggigit bibirnya. Mengambil kertas kecil itu lalu meremasnya. Dengan
langkah gontai, dia berjalan mendekati pohon sakura yang masih mekar. “Novel”
yang dia tulis benar-benar selesai. Dengan kematian sang putri sebagai puncak
cerita, kisah roman itu benar-benar akan menjadi sebuah kisah yang menyentuh. Tidak
hanya menyentuh, tetapi juga mencabik-cabik dan membuat hati setiap pembacanya
hancur. Dan kini, Oreki sedang mempersiapkan ending-nya.
Dengan tatapan mata yang kosong, Oreki mengeluarkan sebuah pisau dari
saku jaketnya. Kepalanya mendongak. Mengizinkan matanya menatap kelopak-kelopak
sakura itu terakhir kali dengan bulir-bulir air mata yang menetes. Dengan satu
gerakan, dia menghujamkan pisau itu ke dada kirinya. Tepat mengenai jantungnya.
Beberapa detik kemudian, tubuhnya terhempas ke tanah. Sebuah kelopak sakura
jatuh di atas wajahnya yang tersenyum bahagia.
Maafkan aku, cinta
Seharusnya aku meminum teh beracun
yang tersisa saat itu juga
Agar aku bisa menghadapi
kematian bersamamu
Bukan menghadapinya sendirian
seperti ini
Semoga di kehidupan
berikutnya nanti, aku bisa kembali bertemu denganmu
Bukan sebagai sosok yang
berperan sebagai pencabut nyawa
Tapi menjadi seseorang yang
mencintaimu
Tanpa kebohongan
Tanpa motif
Tanpa kepura-puraan
Murni sebuah kejujuran
Mencintaimu karena … aku mencintaimu
~ fin ~